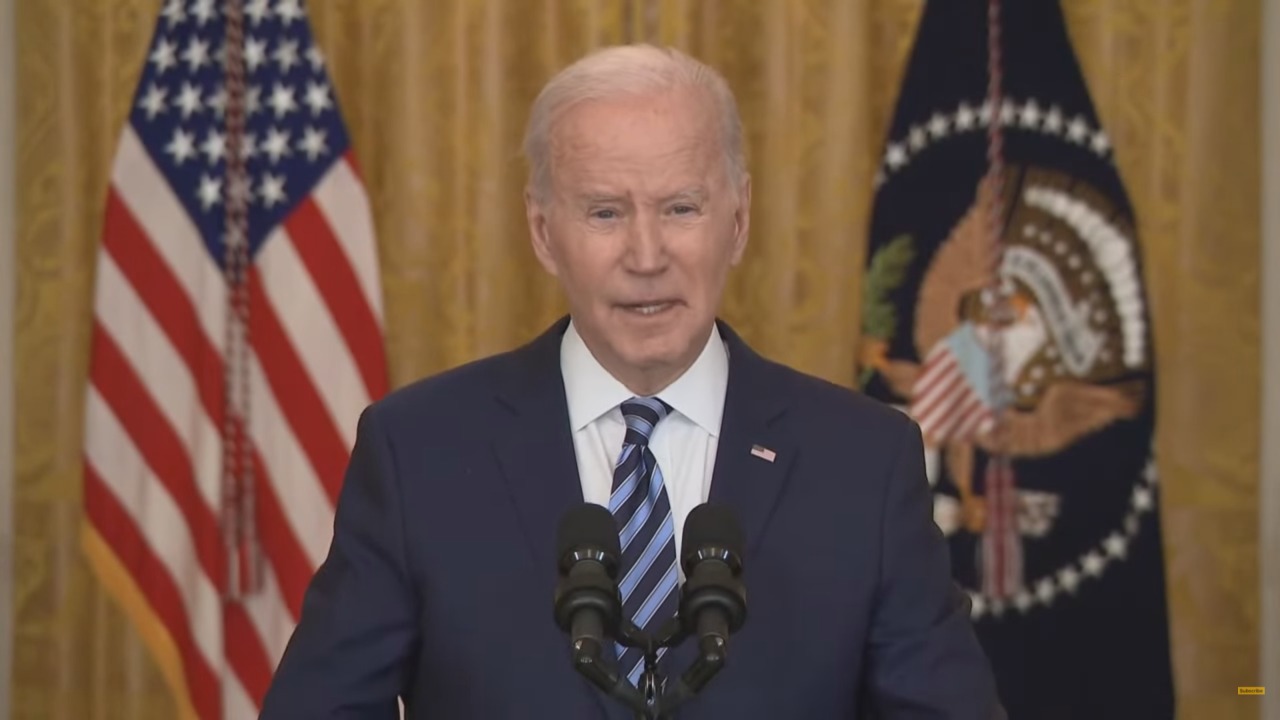Oleh Ryan Kiryanto, Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan
SAAT ini seluruh warga dunia tercengang dengan agresi militer Rusia ke Ukraina. Sebuah kenyataan pahit tidak hanya bagi Ukraina, melainkan juga dunia. Di saat suara perdamaian dunia menggema, justru terjadi situasi perang antara dua negara di Eropa Timur. Kini muncul banyak spekulasi terkait masa depan Ukraina pasca agresi Rusia.
Di sisi lain, sejumlah negara sekutu Eropa dan Amerika Serikat (AS) menentang keras agresi Rusia, bahkan telah menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia. Contohnya Inggris yang telah melarang penerbangan reguler pesawat Rusia. AS pun telah menjatuhkan sanksi pembekuan transaksi perbankan terkait dengan Rusia. Terakhir terbetik kabar Uni Eropa (UE) ingin memutuskan semua hubungan antara Rusia dan sistem keuangan global.
Menghapus Rusia dari sistem antarbank SWIFT (jaringan antarbank global) yang berbasis di Belgia masih menjadi upaya terakhir. Keputusan ini diambil segera setelah para pemimpin nasional Eropa menyetujui sanksi lanjutan terhadap Rusia atas agresinya ke Ukraina.
Uni Eropa ingin memutuskan semua hubungan antara Rusia dan sistem keuangan global untuk mengisolasi Rusia secara finansial sekaligus mengeringkan sumber pembiayaan. Mereka juga bersikeras bahwa pihaknya sudah memiliki blokade lengkap terhadap bank-bank Rusia, yang berarti transaksi bisnis dengan Rusia bisa dikatakan telah dihentikan.
Pilihan sulit dan dilematis
Keputusan drastis yang tergolong sulit dan dilematis bagi mereka itu harus diambil untuk menekan aneksasi Rusia ke negara tetangganya. Artinya, memutuskan Rusia dari sistem dapat memperumit perdagangan yang ada dengan Eropa, termasuk impor gas alam yang penting bagi pasokan energi benua Eropa, selain mempersulit juga pengiriman minyak.
Untuk itu pemerintah Eropa harus siap membuat pilihan sulit dalam menghadapi sikap Rusia. Prancis, sebagai misal, akan melindungi rumah tangga negaranya dari kenaikan harga energi yang mungkin terjadi.
Tensi ketegangan meningkat karena aksi Uni Eropa dan AS itu direspon balik Rusia dengan menerapkan sejumlah sanksi embargo ekonomi. Aksi balas membalas sanksi tersebut dipastikan akan berlarut-larut dan menimbulkan situasi ketidakpastian baru di tengah upaya dunia internasional mengendalikan pandemi Covid-19. Dampak negatif sudah terlihat ketika bursa saham global mengalami koreksi yang dalam pasca serangan Rusia. Mata uang negara-negara berkembang juga terdampak negatif dengan depresiasi yang cukup signifikan.
Situasi yang memburuk di Ukraina memperburuk aksi jual yang sudah suram di perdagangan saham Asia. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik (tidak termasuk Jepang) anjlok lebih dari 3,2%. Bursa saham Australia tersungkur lebih dari 3% dan saham unggulan Tiongkok merosot 1,3%. Indeks Nikkei Tokyo jatuh 2,4%.
Bursa saham global dan imbal hasil obligasi AS merosot tajam. Nilai tukar dolar AS, harga minyak melambung tinggi. Aksi jual ekuitas yang semakin dalam terjadi setelah bursa saham AS terpukul. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) merosot 1,38%. Indeks MSCI World yang menjadi indeks acuan pasar ekuitas global, juga tergelincir ke level terendah sejak April 2021.
Ancaman geopolitik langsung membebani imbal hasil US Treasury 10 tahun, sempat turun tajam menjadi 1,8681% dari penutupan 1,977%. Imbal hasil US Treasury 2 tahun juga turun, menjadi 1,5% dari penutupan 1,6%.
Pasar aset telah melihat peningkatan tajam dalam volatilitas selama krisis yang semakin dalam. Indeks Volatilitas Cboe, yang dikenal sebagai pengukur ketakutan bursa Wall Street, naik lebih dari 55% selama sembilan hari terakhir.
Harga minyak mentah Brent, yang sempat naik turun tajam, tiba-tiba melonjak lebih dari 3,5% hingga menembus 100 dolar AS per barel, untuk pertama kalinya sejak September 2014. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 4,6% menjadi 96,22 dolar AS per barel, tertinggi sejak Agustus 2014. Harga emas di pasar spot juga melonjak lebih dari 1,7% mencapai level tertinggi sejak awal Januari 2021.
Bisa mempengaruhi stance kebijakan moneter
Investor yang tengah menanti kepastian pengetatan kebijakan oleh bank sentral AS, The Federal Reserve Bank, melalui kenaikan suku bunga (Fed Fund Rate/FFR) bertahap untuk menekan laju inflasi yang di level 7%, kini disajikan gambaran suram dengan potensi tambahan kenaikan inflasi global lantaran terganggunya pasokan komoditas. Ekspektasi kenaikan FFR yang agresif sebesar 50 basis poin pada rapat the Fed bulan Maret nanti tetap terjaga, dengan perkiraan kenaikan FFR sebanyak empat-lima kali tahun ini.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi percepatan laju inflasi global setelah terjadi lonjakan harga bahan mentah, barang setengah jadi dan produk jadi menyusul eskalasi gangguan rantai pasok global. Situasi terbaru ini tentu bisa mengubah stance kebijakan ekonomi di sejumlah negara.
Terdapat tiga skenario untuk ekonomi global dari konflik Rusia-Ukraina, dengan implikasi mulai dari sedikit perubahan hingga rencana bank sentral saat ini untuk menarik kembali stimulus moneter era pandemi hingga tinjauan ulang prospek jangka menengah untuk langkah the Fed dan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB).
Implikasinya sangat bergantung pada apa yang terjadi dengan harga energi dan kondisi pasar keuangan. Pada skenario pertama, tidak terjadi perubahan harga energi secara signifikan dengan kondisi pasar keuangan (termasuk pasar obligasi dan ekuitas) yang lebih ketat, tetapi tidak ada aksi jual global yang berkelanjutan dari aset berisiko.
Untuk kawasan Eropa, potensi resesi dapat dihindari, dan kenaikan suku bunga oleh ECB tetap mungkin terjadi di Desember tahun ini. Inflasi bisa menyentuh 3% pada akhir tahun karena ekonomi menanggung biaya energi yang lebih tinggi.
Sementara the Fed akan menerapkan serangkaian kenaikan FFR sebanyak empat-lima kali untuk menekan inflasi menuju jangkar 2% setelah sempat menyentuh level 7%. Peluang kenaikan FFR tersebut sudah price in dengan kebijakan moneter di negara-negara lain dan pelaku pasar pun sudah memperhitungkannya.
Pada skenario kedua, terjadi gangguan terhadap pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia, yang memperburuk guncangan terhadap harga energi global. Inflasi kawasan Eropa bisa menyentuh 4% pada akhir tahun ini yang akan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Ada kans ECB akan menaikkan suku bunga acuan yang pertama pada awal 2023.
Di AS, inflasi bisa menyentuh 9% pada Maret dan berakhir mendekati 6% di akhir tahun. Kondisi pasar keuangan yang lebih ketat dan ekspor yang lebih lemah ke Eropa berpotensi memperlemah pertumbuhan ekonomi. Efeknya, the Fed kemungkinan tetap akan menaikkan FFR, namun tidak seagresif yang diperkirakan semula, dalam artian laju pengetatannya lebih lambat pada paruh kedua 2022.
Pada skenario ketiga, untuk menghadapi sanksi maksimal dari AS dan Eropa, Rusia bisa membalas dengan mematikan semua aliran gas ke Eropa. ECB memperkirakan bahwa guncangan penjatahan gas sebesar 10% dapat memangkas produk domestik bruto (PDB) kawasan Eropa sebesar 0,7%.
Dengan lebih dari 40% gas Eropa berasal dari Rusia, maka sanksi Rusia akan menekan PDB kawasan Eropa sebesar hampir 3% sehingga berpotensi menuju resesi. Alhasil, kenaikan suku bunga ECB akan ditunda ke waktu-waktu mendatang secara tidak terbatas.
Dari masing-masing skenario tersebut, pada intinya tetap menciptakan implikasi kurang menguntungkan bagi para pengambil kebijakan karena kini variabel penentu langkah kebijakan ke depan menjadi makin kompleks, yakni risiko geopolitik yang meningkat dengan transmisi dampaknya melalui jalur keuangan, investasi dan perdagangan global.
Beberapa bank sentral negara-negara maju yang sedianya sudah menyiapkan kebijakan moneter ketat (hawkish policy), mungkin sedikit tertahan dan berubah arah menjadi lebih lunak (dovish policy). Sebagaimana diketahui, kondisi ekonomi AS dinilai cukup sehat sehingga suku bunga acuan harus naik dari level nol persen saat ini menjadi 1% pada musim panas.
Masuk akal jika salah seorang petinggi the Fed menyatakan besaran kenaikan FFR yang pertama (Maret 2022) bisa dua kali lebih besar dari biasanya. Namun, di sisi lain, kembali bahwa invasi Rusia ke Ukraina mengancam kenaikan harga komoditas global dan mengganggu jalur pemulihan ekonomi AS di saat inflasi tinggi.
Maka, the Fed mungkin harus mengubah rencananya untuk mengakhiri “kebijakan uang longgar” yang diterapkan untuk mendukung perekonomian, seiring penyebaran varian baru Covid-19. Diperkirakan inflasi tetap tinggi dan hanya menunjukkan sinyal perlambatan selama beberapa bulan ke depan. Akibatnya, kebijakan FFR yang tepat membawa kisaran target hingga 1%-1,25% di awal musim panas.
Catatan penutup
Langkah senada dengan the Fed yang telah disiapkan oleh bank sentral global menuju kebijakan moneter lebih ketat pasca pandemi kini diragukan kembali sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina. Ini lantaran tensi geopolitik kemungkinan akan dirasakan secara berbeda di seluruh pusat ekonomi utama dunia.
Para pembuat kebijakan bank sentral kini menghadapi risiko global, termasuk lonjakan harga minyak yang signifikan dan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan dalam jangka menengah-panjang akibat krisis Ukraina terhadap kepercayaan, investasi, perdagangan, dan sistem keuangan global.
Selama ini bank-bank sentral negara maju (advanced economies) telah mengambil posisi untuk melawan inflasi, sambil mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan terus berlanjut. Tapi sekarang, mereka mungkin akan melihat pertumbuhan ekonomi melemah, lebih-lebih ketika tingkat harga terus melonjak. Teka-teki ini tidak mudah diselesaikan dengan strategi kebijakan moneter konvensional.
Inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat the Fed, ECB, dan Bank of England (BoE) kesulitan untuk sepenuhnya menghentikan langkah bersama menuju kebijakan moneter yang lebih ketat. Skenario penyesuaian suku bunga bank-bank sentral ini akan direspon dengan stance yang sama oleh bank-bank sentral di emerging markets, khususnya di kawasan Asia.
Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ), secara konsisten masih menjaga kebijakan moneter ultra-longgar, yakni negative reference rate, meskipun dibayangi kenaikan harga energi yang berpotensi mendorong inflasi mendekati target 2%. Pendek kata, BoJ akan mempertahankan status quo untuk beberapa waktu ke depan.
Maklum, kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang berkelanjutan akan memukul ekonomi beberapa negara Asia, karena melemahkan neraca berjalan dan neraca fiskal, serta menekan pertumbuhan. India, Thailand dan Filipina diperkirakan akan menjadi negara yang terdampak serius.
Di sisi lain, bank-bank sentral di negara maju Asia kemungkinan tetap akan memperketat kebijakan karena risiko efek putaran kedua di tengah ekonomi yang sudah menguat. Sementara itu, bank-bank sentral di negara berkembang Asia kemungkinan akan memprioritaskan pertumbuhan yang masih lemah.
Untuk Indonesia, pilihan pada kebijakan yang longgar dan pro pertumbuhan sepertinya merupakan langkah bijak yang tepat untuk tetap dapat menopang momentum pertumbuhan senyampang inflasi masih di bawah jangkar yang sebesar 3%. Pilihan pada kebijakan non suku bunga acuan seecara bertahap dan terukur masih dimungkinkan diambil karena efek risikonya yang jauh lebih terkendali. (*)