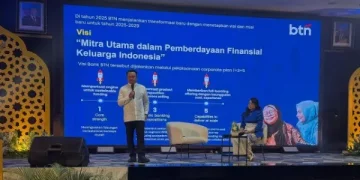(Bagian 1)
Oleh Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
SEJAK terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pascaterbitnya Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk pertama kalinya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Sjamsul Nursalim (ISN) berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019. Sebelum dilakukannya revisi terhadap UU KPK No. 30 Tahun 2002, KPK tidak diberikan wewenang secara atributif untuk menerbitkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU No. 30/2002). Ada plus-minus atau kelebihan dan kekurangan/kelemahan KPK tidak diberikan wewenang menerbitkan SP3.
Kelebihannya, satu, KPK menjadi institusi penegak hukum yang powerfull dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor), karena wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sepenuhnya ada pada KPK (vide Pasal 12 UU No. 30/2002) sebagai suatu hal yang berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan (yang diberikan kewenangan menerbitkan SP3) yang dinilai banyak menemui hambatan dalam menangani perkara tipikor yang dilakukan secara konvensional.
Dua, KPK menjadi institusi yang super (superbody), karena KPK – dalam keadaan tertentu – dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.
Tiga, sebagai institusi penegak hukum yang powerfull dan superbody, KPK diharapkan menunjukkan kinerjanya secara maksimal dalam melaksanakan tugas-wewenangnya dengan cara yang extraordinary untuk memerangi dan memberantas korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime).
Sementara, kekurangan/kelemahannya, tidak diberikannya wewenang secara atributif kepada KPK untuk menerbitkan SP3 dimaksudkan agar KPK hati-hati di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bila belum ada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Jika KPK tidak hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, bahkan tindakan sewenang-wenang, terbuka lebar di balik dalih tidak berwenangnya KPK menerbitkan SP3. Terlebih lagi pasca penetapan seseorang sebagai tersangka dibiarkan berlarut-larut tanpa ada proses hukum lanjutan.
Hal yang demikian itu tentu saja sangat merugikan orang-orang atau mereka yang sudah (telanjur) ditetapkan sebagai tersangka. Selain sudah terjadi pembunuhan karakter (character assassination) sejak seseorang diumumkan oleh KPK sebagai tersangka, juga telah menimbulkan “kematian perdata” yang dialami oleh orang/mereka yang menyandang tersangka berlarut-larut. Last but not least, tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi orang yang menyandang status sebagai tersangka yang dibiarkan berlarut-larut.
Dengan menunjuk konstatasi kelemahan tersebut itulah yang menjadi alasan utama diberikannya wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3 berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 19/2019.
Terbitnya SP3 KPK terhadap SN dan ISN tidak dapat dilepaskan dengan perkara tipikor yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) – mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) – yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam konteks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap SN dan ISN yang dinilai merugikan keuangan negara berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2017.
Terhadap perkara tipikor SAT, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi membebaskan SAT dari segala tuntutan hukum karena perkara SAT tidak atau bukan masuk ranah Hukum Pidana, melainkan masuk ranah Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Atas putusan kasasi tersebut, KPK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dan Majelis Hakim PK menolak permohonan PK yang diajukan oleh KPK.
Bersambung ke bagian 2 >>>>
*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung