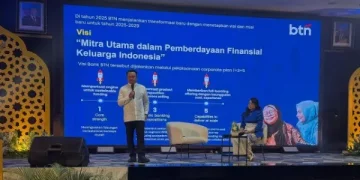Jakarta — Ahli hukum Prof. I Gde Pantja Astawa merasa prihatin dan khawatir atas dampak yang timbul dari pengajuan PK oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari segala tuntutan hukum. Ditegaskannya, tidak ada legal standing bagi Jaksa KPK karena Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan jelas telah menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
“Jaksa KPK tidak punya hak untuk menafsirkan norma dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP,” tukasnya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Selain itu, lanjutnya, penafsiran yang dilakukan Jaksa KPK telah melanggar asas/prinsip hukum yang bersifat universal “interpretatio cessat in claris” yang mengandung arti, kalau teks atau redaksi suatu UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. “Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang telah jelas, berarti penghancuran (interpretatio est perversio), selain menimbulkan ketidakpastian hukum. MA dalam surat keputusannya pun sudah memberikan petunjuk yang jelas bahwa hanya terpidana atau ahliwarisnya yang dapat mengajukan PK. MA harus konsisten dengan keputusannya sendiri dengan menyatakan PK tersebut tidak dapat diterima demi wibawa hukum dan kepastian hukum,” tegas Prof Gde Pantja.
Seperti diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 28 Februari 2020 menyudahi pemeriksaan permohonan Pengajuan Kembali (PK) oleh Jaksa KPK terhadap putusan kasasi MA yang melepaskan SAT dari segala tuntutan hukum. Pengadilan menerima kesimpulan pemeriksaan perkara dari Jaksa KPK dan penasehat hukum SAT. Pengadilan selanjutnya akan meneruskan permohonan PK tersebut ke MA untuk diputuskan.
Prof Gde Pantja Astawan menyatakan, sependapat dengan keterangan ahli Hamdan Zoelva dan Chairul Huda dalam persidangan PK tersebut. “Begitu juga dengan pandangan Prof Seno Adji di media massa,” jawab Prof Gde ketika diminta menanggapi persidangan pengajuan PK di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut.
Hamdan Zoelva dalam persidangan (14/2/2020) menerangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 (“Putusan MK No. 33”), MK telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tersebut. Dalam keputusan tersebut, ditegaskan bahwa PK hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian telah jelas bahwa subyek yang berwenang mengajukan PK bukanlah Jaksa. Mantan Ketua MK tersebut menambahkan, MK telah menegaskan manakala pasal ini dimaknai lain dari yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 263 tersebut adalah inkonstitusional.
Adapun ahli Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H., dalam persidangan berpendapat Putusan MK No. 133 sudah tepat, dimana MK menegaskan bahwa norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma itu sendiri, sehingga tidak boleh ditafsirkan lain. Ahli hukum acara pidana dari Universitas Muhamadyah Jakarta tersebut menerangkan bahwa skema PK di desain hanya untuk terpidana dalam rangka mengoreksi putusan kasasi. Chaerul juga merujuk Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 268 Tahun 2019 yang dengan jelas menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk mengajukan PK.
Pendapat kedua ahli di persidangan senada dengan pandangan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji, dalam berbagai media massa beberapa waktu yang lalu. Ia menyatakan bahwa KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi subjek pemohon PK yang limitatif, yaitu terpidana atau ahli warisnya. PK bukanlah hak dari penegak hukum.
Menurut Prof. Seno Adji, berdasarkan sejarahnya, PK lahir dalam sistem hukum pidana Perancis, dimana prinsipnya, PK atau revition digunakan sebagai basis perlindungan hak asasi manusia, khususnya rakyat yang mendapat perlakuan kesewenangan hukum dari penguasa. Intinya, PK ini hanya diberikan haknya kepada masyarakat yang jadi korban kesewenangan kekuasaan. Bukan diberikan kepada negara, dalam hal ini penegak hukum.
Sementara Prof I Gde Pantja Astawa menegaskan, dari sisi formalitas pengajuan PK telah melanggar hukum. “Secara substansi pun permohonan PK tersebut tidak membantah isi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi. Salah satu yang saya soroti adalah pendapat Majelis Kasasi bahwa Laporan Audit Investigasi BPK tahun 2017 yang menyatakan ada kerugian negara adalah tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diatur dalam Peraturan BPK,” tegasnya.
Prof Gde yang juga mantan anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menerangkan bahwa dalam pelaksanaan audit investigasi harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas informasi atau bukti dari berbagai pihak-pihak terkait, termasuk informasi dari SAT sebagai pihak yang diaudit. Namun kenyataannya, audit investigasi BPK tahun 2017 hanya menggunakan informasi dari satu sumber, yaitu dari penyidik KPK.
“Laporan audit investigasi tahun 2017 ini dalam pelaksanaan investigasinya hanya menggunakan informasi dari satu sumber saja, yaitu Penyidik KPK, dan mengabaikan isi Laporan Audit Investigasi BPK tahun 2002 yang tidak menemukan adanya kerugian negara. Audit investigasi 2017 ini kan audit yang melecehkan akal sehat, namun dipaksakan dan dianggap bukti kuat oleh KPK,” tuturnya.
Sebagai mantan anggota MKKE BPK yang juga mendapat ‘informasi internal’ seputar pelaksanaan audit BPK 2017, Prof Pantja menilai pemeriksa yang melakukan audit investigasi tahun 2017 ini telah melanggar kode etik BPK yang mengharuskan ia melaksanakan pemeriksaan secara independen, berintegritas, dan profesional. “Bagaimana dikatakan independen, berintegritas, dan profesional kalau proses pemeriksaan hanya menggunakan informasi dari satu sumber dan di buat di bawah tekanan pihak-pihak tertentu?” tanya Prof Gde menutup keterangannya. (*)