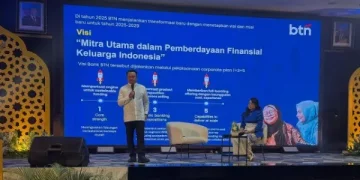Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut para bankir main aman saja. Disebut lazy bank. Tidak berani mengucurkan kredit, meski sudah diguyur likuiditas. “Paceklik kredit” ketika musim hujan likuiditas. Bayangkan. Pemerintah sudah mengguyur likuiditas ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp276 triliun, toh kredit masih stagnan. Bahkan, angka undisbursed loan makin “gendut”. Dan, akhirnya pemerintah menarik kembali dana sebesar Rp75 triliun.
Seretnya kredit, menurut keterangan Purbaya karena para bankir main aman saja. Tidak berani “kencing” kredit dengan frekuensi yang lebih sering. Namun jika memperhatikan angka undisbursed loan yang naik, maka bukan bankirnya yang tidak mengucurkan kredit, tapi memang dunia usaha yang mengerem pencairan.
Banyak faktor, salah satunya masifnya kriminalisasi kredit macet di daerah-daerah. Juga, karena dunia usaha sedang tampak bingung dengan berbagai pelaku bagi dunia usaha besar.
Apalagi, penarikan dana Rp75 triliun dari bank-bank merupakan signal bahwa keuangan negara tampak sedang “butuh uang” untuk membiayai pengeluaran. Disiplin fiskal sedikit kendor, karena hampir seluruh program pemerintah membutuhkan kucuran dana.

Simak saja! Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp698,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bukan sekadar angka statistik. Ia adalah cermin dari pilihan politik dan paradigma ekonomi yang dianut pemerintah. Angka yang nyaris menembus ambang batas psikologis 3 persen ini harus dibaca sebagai tanda peringatan serius, bukan sekadar konsekuensi dari situasi eksternal yang sulit.
Ujian Akhir Fiskal
Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, ada tiga hal penting tentang kondisi fiskal yang memasuki babak genting.
Satu, struktur defisit ini mengungkap ketimpangan mendasar antara ambisi belanja dan kapasitas fiskal. Realisasi pendapatan negara hanya mencapai 91,7 persen dari outlook, dengan kinerja penerimaan pajak yang sangat mengecewakan (87,6 persen dari target).
Jelas ini adalah indikator gagalnya reformasi perpajakan dan lemahnya basis ekonomi produktif. Di sisi lain, belanja negara mampu direalisasikan hingga 95,3 persen dari outlook. Pola ini konsisten dengan karakter anggaran yang expenditure-driven, bukan revenue-driven. Artinya, pemerintah lebih lincah dalam membelanjakan daripada dalam memobilisasi pendapatan. Dalam bahasa politik, ini adalah pilihan untuk memenuhi tuntutan jangka pendek (melalui belanja program prioritas) dengan mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Dua, narasi bahwa defisit diperlukan untuk menjaga ekonomi dari “morat-marit” adalah argumen yang berbahaya jika tidak disertai dengan disiplin eksekusi. Pernyataan Menteri Keuangan bahwa defisit nol bisa dicapai dengan memotong anggaran, tetapi akan membahayakan ekonomi, adalah separuh kebenaran. Separuhnya lagi yang kritis adalah: bagaimana kualitas dan produktivitas belanja yang menjaga ekonomi itu?
Menurut Infobank Institute, persoalannya adalah belanja pemerintah yang belum sepenuhnya produktif. Banyak program “prioritas” lebih bersifat populistik dan konsumtif, bukan investatif. Uang rakyat dibelanjakan untuk menciptakan pertumbuhan semu yang bergantung pada konsumsi, bukan untuk membangun fondasi produktivitas yang solid seperti riset, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur logistik yang efisien.
Tiga, konsekuensi terberat dari defisit ini adalah penyempitan ruang fiskal masa depan melalui beban utang. Menurut data Infobank, pada tahun 2026 utang jatuh tempo membengkak menjadi hampir Rp834 triliun. Jelas ini adalah jerat fiskal. Defisit hari ini akan dibayar dengan utang baru beserta bunganya di masa depan.
Nah, dalam konteks geopolitik yang tidak menentu dan suku bunga global yang tinggi, biaya roll over utang ini akan sangat mahal. Ruang fiskal untuk manuver di masa krisis akan semakin sempit karena anggaran terbebani oleh pembayaran utang. Kita sedang meminjam kemakmuran masa depan untuk dibelanjakan hari ini, dengan jaminan yang belum tentu ada.
Defisit 2,92 persen adalah lampu kuning. Ia mengingatkan bahwa kita sedang berjalan di tepi jurang fiskal. Tanpa koreksi fundamental dalam politik anggaran, tanpa disiplin yang keras, dan tanpa visi ekonomi jangka panjang yang jelas, lampu hijau untuk krisis fiskal suatu saat akan menyala. Kita tidak boleh membiarkan beban itu diwariskan kepada generasi mendatang hanya karena ketidakmampuan membuat pilihan politik yang tepat dan berani hari ini, kecuali nafsu belanja yang membabi buta.
Ujian akhir disiplin fiskal harus dilakukan. Dari sudut pandang ekonomi politik, ini adalah gejala dari pemerintahan yang terjepit antara tuntutan legitimasi populis dan kewajiban menjaga stabilitas makroekonomi. Tekanan untuk menunjukkan kinerja melalui program-program yang terlihat (visible projects) seringkali mengalahkan pertimbangan efisiensi dan keberlanjutan.
Koalisi politik yang berkuasa membutuhkan alat distribusi berupa belanja negara untuk menjaga dukungan. Sementara penerimaan pajak yang optimal sering terhambat oleh resistensi dari kelompok kepentingan (elite bisnis) dan inefisiensi birokrasi.
Lazy Bank, Pidana Kredit Macet, dan Bingungnya Sektor Riil
Ada gula ada semut. Jika dunia usaha subur, maka bank akan dikerubutin semut. Menurut catatan Biro Riset Infobank, penambahan jumlah uang beredar dengan niat mendorong pertumbuhan ekonomi menuai hasil undisbursed loan meningkat.
Lihat saja pada November 2025 angkanya sudah terbang Rp2.509,4 triliun. Atau, naik dari Rp2.372,1 triliun atau 22,71 persen pada Agustus 2025. Jelas ini dunia usaha tidak yakin akan usahanya jalan. Ragu-ragu dan bimbang atas perkembangan politik akhir-akhir ini.
Likuiditas bukan lagi masalah. Tapi, angka pertumbuhan kredit (November 2025) dari data yang sama menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,74 persen. Angka ini lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 lalu yang sebesar 10,79 persen. Jadi, bisa disebut selain karena rendahnya permintaan kredit sejatinya telah terjadi jual beli kredit dari bank Himbara dengan bank-bank yang lebih kecil dengan iming-iming penurunan suku bunga dan kenaikan plafon kredit.
Pertanyaan sederhana ini membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Kita harus berani membedah jauh melampaui narasi teknis-moneter. Ini bukan lagi soal harga uang (suku bunga). Tapi sudah masuk ke ranah ekonomi politik yang rumit. Ada trauma dan kekuasaan “bermain”. Signal yang dikirim oleh pemerintah sering kali membuat takut dunia usaha. Kelompok usaha besar (kelas konglomerat) mulai ketakutan kena palak, baik “resmi” maupun “tidak resmi”.
Jelas itu berdampak pada ketidakpastian, ketakutan, ketidakjelasan, dan kegamangan. Akibatnya, sektor riil bimbang, ragu dan kehilangan arah, kehilangan kepercayaan serta wait and see. Jadi, akarnya di sektor riil. Pendek kata, bukan sekadar lesu, tapi lumpuh struktural. Sektor imajiner yang dikendalikan oleh pemerintah tidak memberi ruang harapan. Jadi lebih baik “diam” dulu dari ekspansi.
Sektor riil kita sedang dilanda penyakit kronis yang akut. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang berubah-ubah seperti bulan-bulanan telah menciptakan kegamangan investasi. Daya saing yang kian tergerus oleh biaya logistik tinggi, biaya ketidakpastian hukum, dan hambatan birokrasi memupuk kekhawatiran mendalam.
Pengusaha bertanya: untuk apa membangun pabrik baru atau ekspansi jika iklim usahanya sendiri tidak ramah dan penuh jebakan? Ini bukan lagi soal business cycle biasa, tapi soal ketakutan eksistensial untuk bertahan. Hasilnya dapat ditebak. Kebimbangan untuk mengambil keputusan investasi, keraguan terhadap masa depan, kehilangan gairah berusaha. Dan — yang paling berbahaya, kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara menyediakan ekosistem usaha yang adil dan stabil.
Reaksi paling rasional dalam kondisi seperti ini adalah wait and see, atau lebih ekstrem lagi, memindahkan aset dan aktivitas ke yurisdiksi yang lebih dapat diprediksi. Logika sederhana ini yang dipahami setiap pengusaha, namun tampaknya kurang dipahami oleh para perancang kebijakan di “menara gading”.
Akibatnya, dunia usaha sering mendengar “Kita akan… Kita akan dan Kita akan”. Tanpa dapat diterjemahkan oleh para teknokrat di sekeliling Presiden. Lalu, lenyap lagi ditelan oleh kata yang sama dengan nuansa yang berbeda, “Kita Akan…Kita Akan”.
Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, di sisi penyalur kredit (bank), terdapat hal penting yang juga sama akutnya. Apa itu? Ada trauma kolektif kalangan perbankan terhadap kredit macet. Ini bukan trauma biasa. Ini adalah trauma yang diperparah oleh fenomena kriminalisasi kegagalan kredit. Ketika seorang bankir bisa diancam dengan pasal pidana atas suatu kredit bermasalah—yang dalam bisnis perbankan adalah risiko intrinsik—maka naluri pertahanan diri akan mengambil alih. Bahkan, debiturnya pun juga kena pasal merugikan negara.
Untuk apa mengambil risiko menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dinamis namun berisiko (seperti UMKM atau startup), jika konsekuensinya bisa berujung di penjara? Lebih aman “mengubur” uang di Surat Utang Negara (SUN) atau ditempatkan di Bank Indonesia (BI) melalui instrumen moneternya. Dana menganggur (undisbursed loan) yang tinggi adalah cermin dari psikologi risk aversion ekstrem ini. Bank menjadi “penonton yang sangat hati-hati”, bukan “pemain” di lapangan ekonomi.
Di tengah lingkungan usaha seperti itu, tentu istilah lazy bank yang dituduhkan tidak selamanya benar. Harus dilakukan bank-bank memang bermain aman dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Penyakit “malas” ini sudah lama terjadi di kalangan bankir. Dan, makin hari makin malas karena lingkungan usaha yang tak pasti dan palu kriminalisasi kredit macet punya caranya sendiri.
Jadi, meski bankir malas atau lazy bank, tapi tentu tidak bisa disalahkan semata kepada para bankir. Pemerintah harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, yaitu memperbaiki iklim usaha dan paling penting urusan kredit macet tentu bukanlah pidana. Jika Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Key Performace Indicator (KPI) dengan banyaknya kasus, dan KPI termudah ketika mengusut kredit macet dari perdata menjadi pidana.
Apalagi, APH melihat masalah ketika kredit sudah macet. Tapi, bankir melihatnya ketika usaha sedang bagus dan punya prospek. Jelas ini berbeda, dan pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan ini. Siapa yang mau, ketika kredit diberikan tahun 2012, misalnya. Lalu, macet di tahun 2025. Sementara para pemutus kredit sudah pensiun, tapi tetap diseret untuk mempertannggung-jawabkan keputusannya.
Lazy bank yang terjadi sekarang ini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu masih ada tanda-tanda kredit dikucurkan dengan lebih kencang. Sekarang, tanda-tanda mengcurkan kredit masih tetap ada, meski kecil plus sektor riilnya juga takut. Ya, bankirnya takut, sektor riilnya juga sama takutnya — ngeri dikriminalisasi. Pasal menguntungkan pihak lain merupakan hantu yang sedang bergentayangan di kalangan bankir.
Akhirnya, di tengah ujian akhir dispilin fiskal yang sekarang dalam lampu kuning, masifnya kriminalisasi kredit macet, dan tuduhan lazy bank tentu tidak semata-mata salah bankir. Pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yaitu menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif. Dan, siap-siap, siapa tahu dengan difisit fiskal yang mendekati 3 persen, ada kemungkinan sisa dana pemerintah yang tersisa Rp201triliun bukan berarti tak akan diambil lagi.
Selamat Ulang Tahun ke-47 Infobank