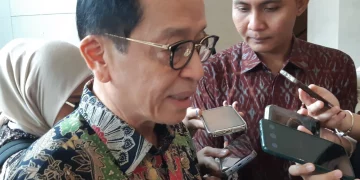Oleh Awaldi : Direktur Operasional Bank Muamalat Indonesia,pengamat pengelolaan SDM, penulis buku berjudul Karyawan Galau Nasabah Selingkuh.
SAYA menonton debat Pilpres (pemilihan presiden) keempat yang dilaksanakan Sabtu tanggal 30 Maret kemaren melalui streaming YouTube di Singapura. Kebetulan saya lagi jalan-jalan ke negeri seberang. Streaming itu disiarkan oleh banyak stasiun TV Jakarta, yang sudah banyak memanfaatkan media YouTube untuk siaran langsungnya.
Debat berlangsung cukup seru, dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Kedua calon presiden beradu gagasan terkait topik cukup sensitif soal ideologi, pemerintahan, pertahanan dan hubungan internasional.
Debat diramaikan dengan tepuk tangan dan teriakan dari tim sukses kedua kubu. Teriakan kedua tim sukses mengiringi debat yang sempat memanas, akan tetapi diakhir acara kedua calon saling memuji. Membalas closing santun Jokowi tentang rantai persahabatan, capres Prabowo menimpalinya “jadi karena ini memang debat pak, ya kan. Audiens kalau melihat kita kalau terlalu bersahabat, mereka enggak (suka). Jadi ini sulitnya memang, ini gimana ya. Saya juga bersahabat dengan beliau (Jokowi), ya gimana, kalau kita berbeda tentang ke negaraan, kan begitu…Kita berjuang bersama-sama untuk rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita”.
Kedua capres mengakhiri debat dengan saling berpelukan dan berjabat tangan. Dan keduanya bersama-sama menyanyikan “Bagimu Negeri” dengan khidmat.
Ponakan saya yg ikut nonton streaming sambil tidur-tiduran karena siangnya jalan-jalan di sekitar Orchards langsung nyeletuk, “pokoknya Prabowo paling pantes. Dia juga pinter nyari pasangan cawapres yang ganteng dan terdidik”.
Dalam bahasa Minang, katanya: “baduo tu iyo takah bana kalau ka jadi pamimpin awak”. Saya Cuma senyum senyum aja.
Adik sepupu saya yang kampungnya jauh di pelosok Jawa Timur sana punya pandangan lain. Katanya, “Jokowi itu orangnya sederhana, rendah hati, toleransi tinggi, dan yang penting merakyat”. Menurut adik sepupu saya Jokowi dan Amin lah yang paling pas untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Pendapat dari ponakan dan adik sepupu itu memang mewakili masing-masing pendukung capres. “Persahabatan” yang diperlihatkan kedua capres pada sesi penutup tetap tidaklah berpengaruh terhadap militansi masing-masing pendukung kedua kubu. Perang tagar dan “perang keyakinan” atas calon yang unggul dalam debat terjadi sangat ramai. Belum debat selesai, laman Facebook sudah dipenuhi komentar kedua kubu. Sama dengan komentar ponakan saya, “apa pun pokoknya nomor dua”. Atau adik sepupu saya, “ya nomer satu lah”.
Saya mempelajari bahwa komentar yang mendukung Jokowi, maupun komentar yang mengunggulkan Prabowo, setidaknya dalam halaman Facebook pertemanan saya, mereka masih orang yang sama yang mendukung salah satu paslon (pasangan calon) sebelum debat berlangsung.
Fenomena yang sama terjadi dalam berbagai jenis platform media sosial yang berbeda, apakah itu Twitter, Linked-in, WhatsApp group; maupun dalam kolom komentar media online mainstream seperti Kumparan, Detik, Infobanknews dan Kompas.
Melalui pengamatan saya, masing-masing pendukung paslon tidak hanya militan atas pilihannya, akan tetapi mereka juga sudah masuk dalam fenomena situasi psikologis yang saya namakan “perangkap keyakinan”. Suatu perangkap yang susah dihindari oleh seseorang yang sudah punya predetermined keyakinan yang sangat kuat. Perangkap ini bisa mencelakakan karena sudah menutup bukan saja mata inderanya, akan tetapi juga mata bathin yang diperlukan untuk membimbing ke arah kehidupan madaniah yang lebih baik.
Keyakinan yang berlebihan membuat distorsi persepsi yang tinggi. Realitas yang kita lihat berkabut. Tidak lagi terlihat jelas aslinya. Sering malah kabutnya “berbau keringat kita sendiri”, terlihat sesuai dengan apa yang ingin kita saksikan.
Dalam percakapan beberapa kali dengan teman di kantor, selalu saya bilang, “tengoklah betapa telah terjadi distorsi besar terhadap mereka yang meyakini bahwa paslon yang satu lebih baik dari yang lain”. Berita hoax bertebaran dan cendrung dipercaya kalau itu terkait dg kejelekan kubu sebelah. Kecendrungannya melihat bahwa kubu sebelah banyak salah dan nggak benernya, dan tentu yang paling bener dan pas adalah kubu yang ada dalam pihaknya. Kesalahan sedikit dari kubu sebelah akan dibesar-besarkan. Kritik terhadap kubunya sendiri akan dianggap suatu serangan dan penghinaan besar, jurus-jurus defensif akan dimainkan, dan segala cara dilakukan untuk meluruskan pandangan “yang dianggap salah” tersebut.
Kepada ponakan saya sampaikan, “kamu bisa bayangkan situasi yang sama akan terjadi akibat militansi keyakinan yang berlebihan, tentang apapun!”.
Terlalu yakin dengan pendapat sendiri, akan membuat kita menutup mata dari kemungkinan kebenaran dari pendapat dan pemikiran orang lain. Akibatnya kita nggak bisa terbuka dan melihat sisi-sisi lain dari suatu fakta. Banyak orang yang selalu bilang, “pokoknya begini!”. Menunjukkan bahwa orang tersebut sulit melangkah maju karena terkunkung dengan kebenaran dirinya sendiri.
Fanatisme yang terlalu kuat terhadap kebesaran satu suku, telah menyebabkan terjadinya keangkuhan satu suku terhadap suku yang lain. Di Indonesia beberapa kali terjadi sentimen kesukuan, contohnya sentimen kesukuan antara Minang dan Batak, atau antara Jawa dan Sunda. Banyak cerita-cerita kerakyatan yang muncul dari fanatisme kesukuan ini. Beberapa di antaranya saya saksikan semasa kuliah di Yogya tahun 80-an, yaitu terjadinya aksi saling serang antara mahasiswa yang beraral dari daerah berbeda.
Perpecahan dan kelamambanan dalam perubahan terjadi karena militansi yang berlebihan atas keyakinan tertentu.
Militansi atas suatu keyakinan adalah bagus, karena kita akan mempunyai kebanggaan berada dalam satu kubu, mempunyai teman-teman yang punya keyakinan yang sama, saling melindungi, saling mensupport karena berada dalam “in-group”.
Akan tetapi “militansi keyakinan” yang berlebihan akan menjadi perangkap kehidupan. Perangkap itu menyebabkan kita berpotensi “berhenti menjadi manusia”; berhenti belajar dan mencari makna kehidupan yang lebih dalam, berhenti menghormati sesama, berhenti melihat sesuatu dari posisi yang berbeda, berhenti menggali makna kebenaran.
Perangkap itu membuat kita stagnan dan berhenti berubah. (*)